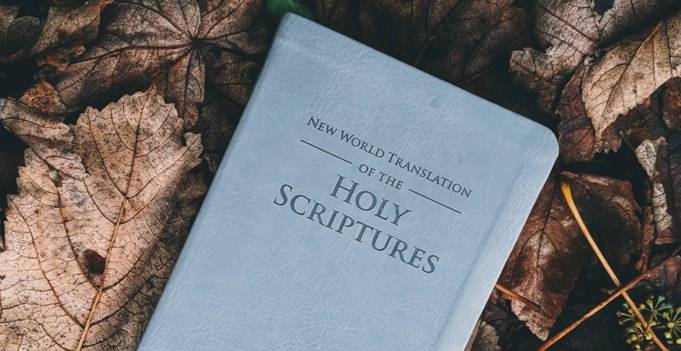Sosial MediaTentang KamiArtikel TerbaruUpdate Terakhir |
Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs SOTeRI Keberadaan AllahPenulis_artikel:
James N. Anderson
Tanggal_artikel:
15 Juli 2022
Isi_artikel:
DEFINISI Eksistensi dan sifat-sifat Allah terlihat dari ciptaan itu sendiri, meskipun manusia berdosa menekan dan mendistorsi pengetahuan alamiah mereka tentang Allah. RINGKASAN Eksistensi Allah menjadi dasar bagi studi teologi. Alkitab tidak berusaha untuk membuktikan keberadaan Allah, melainkan menerimanya begitu saja. Kitab Suci mengungkapkan doktrin yang kuat tentang wahyu alam: keberadaan dan sifat-sifat Allah terbukti dari ciptaan itu sendiri, meskipun manusia yang berdosa menekan dan mendistorsi pengetahuan alami mereka tentang Allah. Pertanyaan dominan dalam Perjanjian Lama dan Baru bukanlah apakah Allah itu, melainkan siapakah Allah itu. Para filsuf, baik Kristen maupun non-Kristen, telah menawarkan berbagai argumen tentang keberadaan Allah, dan disiplin teologi alam (apa yang dapat diketahui atau dibuktikan tentang Allah hanya dari alam) berkembang pesat saat ini. Namun, beberapa filsuf mengemukakan bahwa kepercayaan kepada Allah itu dibenarkan secara rasional bahkan tanpa argumen atau bukti teistik. Sementara itu, orang-orang yang mengaku ateis mengajukan berbagai argumen yang menentang keberadaan Allah; yang paling populer adalah argumen dari kejahatan, yang menyatakan bahwa keberadaan dan tingkat kejahatan di dunia memberi kita cukup alasan untuk tidak percaya kepada Allah. Sebagai tanggapan, para pemikir Kristen telah mengembangkan berbagai teodisi, yang berusaha menjelaskan mengapa Allah secara moral dibenarkan dalam mengizinkan kejahatan yang kita amati. Jika teologi adalah studi tentang Allah dan karya-karya-Nya, keberadaan Allah sama mendasarnya bagi teologi seperti halnya keberadaan batu bagi geologi. Dua pertanyaan dasar diajukan mengenai kepercayaan akan keberadaan Allah: (1) Apakah itu benar? (2) Apakah itu dibenarkan secara rasional (dan jika demikian, atas dasar apa)? Pertanyaan kedua berbeda dari yang pertama karena suatu kepercayaan bisa menjadi benar tanpa dibenarkan secara rasional (misalnya, seseorang bisa saja secara irasional percaya bahwa dia akan mati pada hari Kamis, kepercayaan yang ternyata kebetulan benar). Para filsuf telah bergulat dengan kedua pertanyaan itu selama ribuan tahun. Dalam esai ini, kita akan merenungkan apa yang Alkitab katakan sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, sebelum mengambil sampel jawaban dari beberapa pemikir Kristen yang berpengaruh. Kitab Suci dan Keberadaan Allah
Alkitab diawali bukan dengan bukti keberadaan Allah, tetapi dengan pernyataan tentang karya Allah: "Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi." Penegasan dasar Kitab Suci ini mengasumsikan bahwa pembaca tidak hanya sudah mengetahui bahwa Allah itu ada, tetapi juga memiliki pemahaman dasar tentang siapa Allah itu. Sepanjang Perjanjian Lama, kepercayaan kepada Allah pencipta diperlakukan sebagai hal yang normal dan alami bagi semua manusia, meskipun bangsa-bangsa kafir telah jatuh ke dalam kebingungan tentang identitas sebenarnya dari Allah ini. Mazmur 19 dengan gamblang mengungkapkan doktrin wahyu alam: seluruh alam semesta ciptaan 'menyatakan' dan 'mewartakan' karya-karya agung Allah. Amsal memberi tahu kita bahwa "takut akan Tuhan" adalah titik awal pengetahuan dan hikmat (Ams. 1:7; 9:10; lih. Mzm. 111:10). Oleh karena itu, menyangkal keberadaan Allah secara intelektual dan moral adalah menyimpang (Mzm. 14:1; 53:1). Memang, perhatian dominan dalam seluruh Perjanjian Lama bukanlah tentang apakah Allah itu ada, melainkan siapakah Allah itu. Apakah Yahweh adalah satu-satunya Tuhan yang benar atau tidak (Ul. 4:35; 1Raj. 18:21, 37, 39; Yer. 10:10)? Pandangan dunia yang menjadi landasan bagi monoteisme Ibrani adalah politeisme pagan, bukan ateisme sekuler. Pendirian tentang keberadaan Allah ini berlanjut ke dalam Perjanjian Baru, yang dibangun di atas landasan monoteisme Perjanjian Lama yang tanpa kompromi. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus menegaskan bahwa "kuasa-Nya yang kekal dan sifat keilahian-Nya" jelas terlihat dari tatanan ciptaan itu sendiri. Secara objektif, tidak ada dasar rasional untuk meragukan keberadaan pribadi Pencipta yang transenden, dan dengan demikian tidak ada alasan untuk tidak percaya (Rm. 1:20). Diberkahi dengan pengetahuan alami tentang Pencipta kita, kita berutang hormat dan syukur kepada Allah, dan kegagalan kita untuk melakukannya berfungsi sebagai dasar utama untuk manifestasi murka dan penghakiman Allah. Doktrin sang rasul yang kuat tentang wahyu alam menimbulkan pertanyaan tentang apakah ada orang yang benar-benar bisa menjadi ateis. Jawabannya akan tergantung, pertama, pada bagaimana "ateis" didefinisikan, dan kedua, pada apa tepatnya maksud Paulus ketika dia berbicara tentang orang-orang yang "mengenal" Allah. Jika gagasannya adalah bahwa semua manusia tetap memiliki beberapa pengetahuan sejati tentang Allah, terlepas dari penindasan dosa mereka terhadap wahyu alam, sulit untuk mempertahankan bahwa siapa pun dapat sepenuhnya tidak memiliki kesadaran kognitif tentang keberadaan Allah. Namun, jika "ateis" didefinisikan sebagai seseorang yang menyangkal keberadaan Allah atau mengaku tidak percaya kepada Allah, Roma 1 tidak hanya mengizinkan keberadaan ateis -- pada dasarnya, ia memprediksinya. Ateisme kemudian dapat dipahami sebagai bentuk penipuan diri yang salah. Keyakinan Paulus tentang wahyu alami diterapkan dalam khotbahnya kepada pendengar non-Yahudi di Listra dan Atena (Kis. 14:15-17; 17:22-31). Paulus berasumsi tidak hanya bahwa para pendengarnya mengetahui hal-hal tertentu tentang Allah dari tatanan ciptaan, tetapi juga bahwa mereka telah dengan penuh dosa menekan dan memutarbalikkan kebenaran-kebenaran yang diwahyukan ini, dan justru beralih ke penyembahan berhala terhadap ciptaan (lih. Rm. 1:22-25). Meski begitu, seruannya kepada wahyu umum tidak pernah ditawarkan secara terpisah dari wahyu khusus: Kitab Suci Perjanjian Lama, pribadi Yesus Kristus, dan kesaksian para rasul Kristus. Dalam bagian lain dalam Perjanjian Baru, pertanyaan tentang keberadaan Allah hampir tidak pernah secara eksplisit diangkat, melainkan berfungsi sebagai praanggapan dasar, asumsi latar belakang yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Satu pengecualian adalah penulis surat Ibrani, yang menyatakan bahwa "siapa pun yang datang kepada-Nya harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi pahala kepada mereka yang mencari Dia" (11:6, AYT). Secara umum, Perjanjian Baru kurang memperhatikan pertanyaan filosofis tentang keberadaan Allah dibandingkan dengan pertanyaan praktis tentang bagaimana orang berdosa dapat memiliki hubungan yang menyelamatkan bersama Allah yang keberadaan-Nya jelas. Seperti dalam Perjanjian Lama, pertanyaan yang mendesak bukanlah apakah Allah itu ada, melainkan siapakah Allah itu. Apakah Yesus Kristus adalah wahyu Allah dalam daging manusia atau tidak? Itulah inti masalahnya. Argumen untuk Keberadaan Allah Renungkan kembali dua pertanyaan yang disebutkan di awal. (1) Apakah kepercayaan kepada Allah itu benar? (2) Apakah itu dibenarkan secara rasional? Salah satu cara menarik untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut dengan tegas adalah dengan menawarkan argumen teistik yang berusaha menyimpulkan keberadaan Allah dari hal-hal lain yang kita ketahui, amati, atau anggap remeh. Argumen teistik yang meyakinkan, asumsinya, tidak hanya akan menunjukkan kebenaran tentang keberadaan Allah, tetapi juga memberikan pembenaran rasional untuk memercayainya. Ada banyak literatur tentang argumen teistik, jadi hanya contoh sorotan yang dapat diberikan di sini. Generasi pertama apolog Kristen merasa tidak perlu memperdebatkan keberadaan Allah karena alasan yang sama bahwa tidak seorang pun menemukan argumen seperti itu dalam Perjanjian Baru: tantangan utama teisme Kristen bukan berasal dari ateisme, melainkan dari teisme non-Kristen (Yudaisme) dan politeisme pagan. Baru pada periode abad pertengahan kita menemukan argumen-argumen formal tentang keberadaan Allah ditawarkan, dan argumen-argumen itu pun tidak berfungsi terutama sebagai sanggahan ateisme, melainkan sebagai meditasi filosofis tentang sifat Allah dan hubungan antara iman dan akal budi. Salah satu yang paling terkenal dan kontroversial adalah argumen ontologis St. Anselmus (1033 -- 1109) yang menyatakan bahwa keberadaan Allah dapat disimpulkan hanya dari definisi Allah, sedemikian rupa sehingga ateisme mengarah pada kontradiksi diri. Salah satu ciri khas dari argumen ini adalah bahwa ia bergantung hanya pada akal budi tanpa ketergantungan pada premis empiris. Berbagai versi argumen ontologis telah dikembangkan dan dipertahankan, dan berbagai pendapat terbagi tajam, bahkan di antara para filsuf Kristen, mengenai apakah ada, atau mungkinkah ada, versi yang masuk akal. Argumen kosmologis berusaha untuk menunjukkan bahwa keberadaan alam semesta, atau beberapa fenomena di dalam alam semesta, menuntut penjelasan kausal yang berasal dari penyebab pertama yang diperlukan di luar alam semesta. St. Thomas Aquinas (1225 -- 1274) terkenal menawarkan "Lima Cara" untuk menunjukkan keberadaan Allah, yang masing-masing dapat dipahami sebagai semacam argumen kosmologis. Sebagai contoh, salah satu dari Lima Cara tersebut berpendapat bahwa setiap gerakan (perubahan) harus dijelaskan oleh semacam penggerak (penyebab). Jika penggerak itu sendiri menunjukkan gerakan, harus ada penggerak sebelumnya untuk menjelaskannya, dan karena tidak mungkin ada kemunduran tak terbatas dari penggerak yang digerakkan, harus ada penggerak asli yang tidak bergerak: penyebab pertama yang abadi, tidak berubah, dan ada dengan sendirinya. Pembela argumen kosmologis terkenal lainnya termasuk G.W. Leibniz (1646 -- 1716) dan Samuel Clarke (1675 -- 1729), dan baru-baru ini Richard Swinburne dan William Lane Craig. Argumen teleologis, yang bersama dengan argumen kosmologis dapat ditelusuri kembali ke Yunani kuno, berpendapat bahwa Allah adalah penjelasan terbaik untuk desain atau keteraturan yang nyata di dalam alam semesta. Sederhananya, desain membutuhkan seorang desainer, dan dengan demikian penampilan desain di dalam alam adalah bukti dari seorang desainer supranatural. William Paley (1743 -- 1805) terkenal karena argumennya dari analogi yang membandingkan pengaturan fungsional dalam organisme alami dengan yang ada dalam artefak buatan manusia, seperti arloji saku. Sementara argumen desain mengalami kemunduran dengan munculnya teori evolusi Darwin, yang dimaksudkan untuk menjelaskan desain nyata organisme dalam hal proses adaptif tidak terarah, apa yang disebut Gerakan Desain Cerdas telah menghidupkan kembali argumen teleologis dengan wawasan dari kosmologi kontemporer dan biologi molekuler sambil mengungkap kekurangan serius dalam penjelasan Darwinian naturalistik. Pada abad ke-20, argumen moral memperoleh popularitas yang cukup besar, paling tidak karena penyebarannya oleh C. S. Lewis (1898 -- 1963) dalam buku terlarisnya Mere Christianity ("Sekadar Kekristenan" - Red.). Argumen ini biasanya bertujuan untuk menunjukkan bahwa hanya pandangan dunia teistik yang dapat menjelaskan hukum dan nilai moral yang objektif. Seperti argumen teistik lainnya, ada beragam versi argumen moral, yang memperdagangkan berbagai aspek intuisi dan asumsi moral kita. Karena argumen semacam itu biasanya didasarkan pada realisme moral -- pandangan bahwa ada kebenaran moral objektif yang tidak dapat direduksi menjadi sekadar preferensi atau konvensi manusia -- kerja ekstra sering diperlukan untuk mempertahankan argumen semacam itu dalam budaya tempat kepekaan moral telah terkikis oleh subjektivisme, relativisme, dan nihilisme. Cornelius Van Til (1895 -- 1987) menjadi terkenal karena kritiknya yang keras terhadap "metode tradisional" apologetika Kristen yang menyerah pada "nalar manusia yang otonom". Van Til berpendapat bahwa setiap argumen teistik yang terhormat harus mengungkapkan ketaksangkalan Allah Tritunggal yang diungkapkan dalam Kitab Suci, bukan hanya Penyebab Pertama atau Perancang Cerdas. Oleh karena itu, dia menganjurkan pendekatan alternatif, yang berpusat pada argumen transendental untuk keberadaan Allah, tempat orang Kristen berusaha untuk menunjukkan akal manusia, jauh dari otonom dan mandiri, mensyaratkan Allah Kekristenan, Sang "Pengondisi Segala Sesuatu" yang menciptakan, menopang, dan mengarahkan segala sesuatu menurut hikmat-Nya. Seperti yang dikatakan Van Til, kita harus berargumentasi "dari ketidakmungkinan sebaliknya": jika kita menyangkal Allah Alkitab, kita membuang alasan untuk berasumsi bahwa pikiran kita memiliki kapasitas untuk berpikir rasional dan memiliki pengetahuan yang dapat diandalkan tentang dunia. Sejak kebangkitan filsafat Kristen pada paruh kedua abad ke-20, ada minat dan antusiasme baru terhadap proyek pengembangan dan pembelaan argumen teistik. Versi yang baru dan lebih baik dari argumen klasik telah ditawarkan, sementara perkembangan dalam filsafat analitik kontemporer telah membuka jalan baru bagi teologi alam. Dalam kuliahnya pada 1986, "Dua Lusin (atau lebih) Argumen Teistik", Alvin Plantinga membuat sketsa seluruh argumen untuk Allah mulai dari A sampai Z, yang sebagian besar belum pernah dieksplorasi sebelumnya. Saran Plantinga sejak itu telah diperluas dan dibukukan oleh para filsuf lain. Disiplin teologi natural Kristen berkembang pesat melebihi sebelum-sebelumnya. Keyakinan Dasar tentang Adanya Allah Namun, apakah satu pun dari argumen ini benar-benar diperlukan? Apakah keyakinan tentang keberadaan Allah harus ditopang oleh bukti-bukti filosofis? Sejak Abad Pencerahan, sering dianggap bahwa kepercayaan kepada Allah itu dibenarkan secara rasional hanya jika dapat didukung oleh bukti filosofis atau bukti ilmiah. Sementara Roma 1:18-21 kadang-kadang diambil sebagai mandat untuk argumen teistik, bahasa Paulus dalam bagian itu menunjukkan bahwa pengetahuan kita tentang Allah dari wahyu alam jauh lebih langsung, intuitif, dan dapat diakses secara universal. Dalam bab-bab pembukaan Institutes of the Christian Religion (Pengajaran Agama Kristen atau lebih dikenal sebagai Institutio - Red.) karyanya, John Calvin (1509 -- 1564) mempertimbangkan apa yang dapat diketahui tentang Allah selain dari wahyu khusus dan menegaskan bahwa pengetahuan alam telah ditanamkan secara universal dalam umat manusia oleh Sang Pencipta: "Dalam pikiran manusia, dan betul oleh naluri alami, terdapat kesadaran akan keilahian" (Institutes, I.3.1). Calvin berbicara tentang sensus divinitatis, "rasa terhadap keilahian", yang dimiliki oleh setiap orang karena diciptakan menurut gambar Allah. Kesadaran internal akan Sang Pencipta ini "tidak akan pernah bisa dilenyapkan", meskipun orang-orang berdosa "berjuang mati-matian" untuk menghindarinya. Pengetahuan alami tertanam kita tentang Allah dapat disamakan dalam beberapa hal dengan pengetahuan alami kita tentang hukum moral melalui kemampuan hati nurani yang diberikan Allah (Rm. 2:14-15). Kita tahu secara naluriah bahwa berbohong dan mencuri itu salah; tidak diperlukan argumen filosofis untuk membuktikan hal-hal seperti itu. Demikian pula, kita tahu secara naluriah bahwa ada Allah yang menciptakan kita dan kepada-Nya kita harus memberi hormat dan mengucap syukur. Pada 1980-an, sejumlah filsuf Protestan yang dipimpin oleh Alvin Plantinga, Nicholas Wolterstorff, dan William Alston mengembangkan pembelaan canggih terhadap gagasan Calvin tentang sensus divinitatis. Dijuluki "epistemolog Reformed", mereka berpendapat bahwa kepercayaan teistik dapat (dan biasanya harus) benar-benar mendasar: dibenarkan secara rasional, bahkan tanpa bukti empiris atau bukti filosofis. Pada pandangan ini, percaya bahwa Allah itu ada sebanding dengan percaya bahwa dunia pengalaman kita benar-benar ada; itu sepenuhnya rasional, bahkan jika kita tidak dapat menunjukkannya secara filosofis. Memang, akan sangat disfungsional untuk percaya sebaliknya. Argumen Melawan Keberadaan Allah Bahkan dengan mengakui bahwa ada pengetahuan alam universal tentang Allah, tidak diragukan lagi ada orang yang menyangkal keberadaan Allah dan menawarkan argumen pembelaan mereka. Beberapa orang telah berusaha untuk mengungkap kontradiksi dalam konsep Allah (misalnya, antara kemahatahuan dan kebebasan ilahi) sehingga menyamakan Allah dengan "lingkaran persegi" yang keberadaannya secara logis tidak mungkin. Paling banyak, argumen seperti itu hanya mengesampingkan konsepsi tertentu tentang Allah, yaitu konsepsi-konsepsi yang sering bertentangan dengan pandangan alkitabiah tentang Allah dalam hal apa pun. Pendekatan yang lebih sedikit ambisius adalah menempatkan beban pembuktian pada kaum teis: dengan tidak adanya argumen yang baik untuk keberadaan Allah, seseorang harus mengadopsi posisi ateisme "bawaan" (atau setidaknya agnostisisme). Sikap ini sulit dipertahankan mengingat banyak argumen teistik mengesankan yang diperjuangkan oleh para filsuf Kristen saat ini, belum lagi argumen para epistemolog Reformed bahwa kepercayaan kepada Allah adalah dasar yang tepat. Argumen ateistik terpopuler tidak diragukan lagi adalah argumen dari kejahatan. Versi kuat argumen tersebut menyatakan bahwa keberadaan kejahatan secara logis tidak sesuai dengan keberadaan Allah yang mahabaik dan mahakuasa. Versi yang lebih sederhana berpendapat bahwa contoh kejahatan yang sangat mengerikan dan tampaknya serampangan, seperti Holocaust, memberikan bukti kuat untuk melawan keberadaan Allah. Masalah kejahatan telah mengundang berbagai teodisi: upaya untuk menjelaskan bagaimana Allah dapat dibenarkan secara moral dalam mengizinkan kejahatan yang kita temui di dunia. Meskipun penjelasan semacam itu bisa berguna, penjelasan tersebut tidak sepenuhnya diperlukan untuk membantah argumen dari kejahatan. Cukuplah untuk menunjukkan bahwa mengingat kompleksitas dunia dan keterbatasan pengetahuan manusia yang cukup besar, kita tidak berada dalam posisi untuk menyimpulkan bahwa Allah tidak dapat memiliki alasan yang menjustifikasi secara moral untuk mengizinkan kejahatan yang kita amati. Memang, jika kita sudah memiliki dasar untuk percaya kepada Allah, kita dapat menyimpulkan bahwa Allah pasti memiliki alasan seperti itu, terlepas dari apakah kita dapat memahaminya atau tidak. BACAAN LEBIH LANJUT
|